Ketua DPR dan KPK
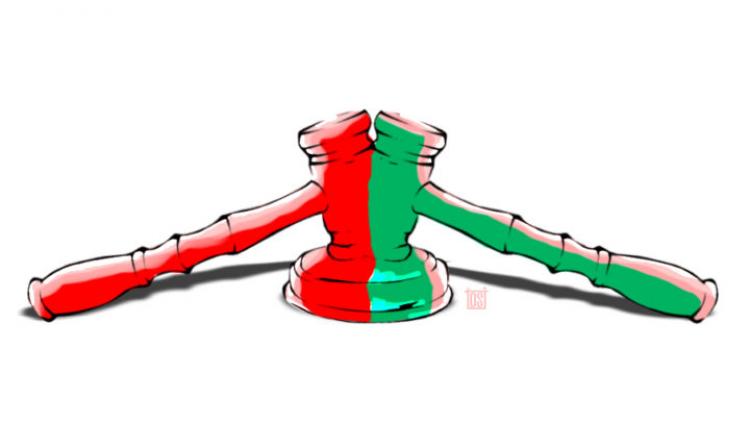
Setelah dilantik, ketua DPR yang baru, Bambang Soesatyo, menyampaikan beberapa rencana kebijakan sebagai orang nomor satu di legislatif. Dua di antaranya adalah menambah kursi pimpinan DPR dan mengakhiri kerja panitia khusus hak angket KPK (Kompas, 16/1/2018).
Menarik membaca lebih serius pernyataan Ketua DPR itu soal merampungkan tugas pansus angket—tentunya dengan tidak menafikan penambahan kursi pimpinan DPR di akhir periode—dan menelaahnya dari kacamata politik hukum ketatanegaraan.
Belok arah
Bambang Soesatyo, sebagaimana dikutip media, menjamin rekomendasi pansus angket tidak akan melemahkan KPK. Bahkan, ia juga menjamin aman UU KPK yang gencar akan direvisi. Ia hanya mengingatkan pimpinan KPK agar membenahi internalnya.
Apakah DPR sedang mengambil ”jalan damai” dengan komisi antikorupsi? Opsi ”menghentikan” kerja pansus angket memang mengejutkan. Pasalnya, di fase awal, banyak anggota Dewan ngotot ingin menyelidiki KPK. Pemeriksaan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan aktor dari sisi legislatif—serta eksekutif dan swasta/korporasi—ditengarai menjadi pemicu niat menginvestigasi komisi antikorupsi. Jika sekarang Ketua DPR mengisyaratkan bakal ”memperhalus” hasil pansus angket, bukankah ini mengagetkan?
Apakah DPR sedang berbelok arah dan memilih menghindari rusuh dengan KPK? Pertanyaan ini harus diuji dengan teliti. Informasi media massa dan fakta yang disuguhkan ke masyarakat untuk mendukung berbeloknya niat legislatif itu sepertinya bernilai sebaliknya.
Dalam bacaan awam, diputus-bersalahnya terdakwa Irman dan Sugiharto, terdakwa korupsi KTP-el dari unsur eksekutif, pada pengadilan tipikor tingkat pertama, naga-naganya menjadi titik awal keruntuhan bangunan niat pansus angket memperpanjang urusan dengan KPK.
Kemudian, rentetan penetapan tersangka oleh KPK terhadap nama-nama anggota Dewan periode 2009-2014, termasuk mantan Ketua DPR, Setya Novanto, dalam korupsi KTP-el, semakin mempercepat luruhnya keyakinan investigatif Pansus terhadap KPK. Puncaknya, boleh jadi, adalah keinginan Setya Novanto untuk menjadi justice collaborator (JC).
Sebagai catatan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4/2011 sebagai pedoman teknis penentuan JC, ada syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa yang meminta. Pertama, ia adalah pelaku. Kedua, mengakui perbuatan pidananya. Ketiga, ia bukan pelaku utama kejahatan.
Artinya, tatkala Setya Novanto mengajukan status JC, dengan sendirinya ia telah mengakui perbuatan pidananya. Belakangan, melalui advokatnya, Setya Novanto juga bertekad membongkar nama-nama besar dari unsur legislatif—dan eksekutif—yang masuk ke kubangan korupsi KTP-el (Kompas.com,11/1/2018).
Opsi kerja sama
Jika meletakkan pemeriksaan persidangan kasus korupsi KTP-el sebagai alur kerja pansus, pernyataan tentang garansi rekomendasi pansus angket yang tidak akan melemahkan KPK dan tidak pula merevisi undang-undangnya adalah pilihan rasional.
Pengalaman dalam pemeriksaan kasus korupsi memberi referensi yang valid bahwa tatkala ada satu tersangka ”bersuara”, hampir bisa dipastikan semua yang menikmati uang korupsi akan dijerat. Tinggal menunggu dan mengatur waktu serta membagi beban penyidikan saja. Semua tinggal antre menunggu diperiksa.
Contohnya, kasus korupsi Hambalang. Kasus ini menjerat terlebih dulu unsur eksekutif dan swasta. Kemudian, menekuk Muhammad Nazaruddin, mantan anggota DPR dan Bendahara Partai Demokrat, meski sebelumnya lari sampai ke Cartagena, Kolombia.
Melawan atau kerja sama
Walau awalnya Nazaruddin ”mogok diperiksa” ke KPK, akhirnya ia ”buka mulut”. Satu per satu nama keluar dari keterangannya, termasuk ketua umum kala itu Anas Urbaningrum, yang dapat dijerat dalam kasus korupsi Hambalang.
Pendek kata, berdasarkan referensi pemeriksaan kasus korupsi, khususnya big fish dan menyita perhatian publik, memang tidak tersedia banyak pilihan ketika berurusan dengan komisi antikorupsi. Bahkan, mungkin hanya ada dua opsi: melawan habis-habisan atau bekerja sama.
Opsi pertama bukanlah opsi brilian. Apalagi kalau hanya melawan KPK melalui jalur politik. Semua tantangan dilewati dan diladeni dengan bertungkus-lumus. Lembaga antikorupsi itu sudah banyak makan asam-garam. Karena itu, opsi yang masuk akal hanyalah bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi.
Oleh karena itu, langkah Ketua DPR memberi isyarat hendak mengakhiri saga angket KPK dengan mulus, tanpa konflik, harus dijadikan momentum untuk meluruskan arah. Ketua DPR harus menjadi panglima pembersihan legislatif dari tindakan koruptif. Sinergi pemberantasan korupsi antara DPR dan KPK bakal luar biasa.
DPR seyogianya menjalankan kekuasaan rakyat dengan bijaksana. Melayani rakyat melalui pembentukan undang-undang yang menyejahterakan. Menguliti KPK dengan dalih macam- macam hanya membuat anggota Dewan terlihat tak bijaksana. Ketua DPR baru punya kesempatan untuk menyetir Senayan ke arah yang lebih bijak. Itu adalah soal amanah, bukan sekadar kekuasaan.
Hifdzil Alim Ketua LPBH PWNU DIY; Peneliti di Pukat FH UGM
Tulisan ini disalin dari Harian Kompas, 25 Januari 2018










