Setengah Hati Berantas Mafia Peradilan
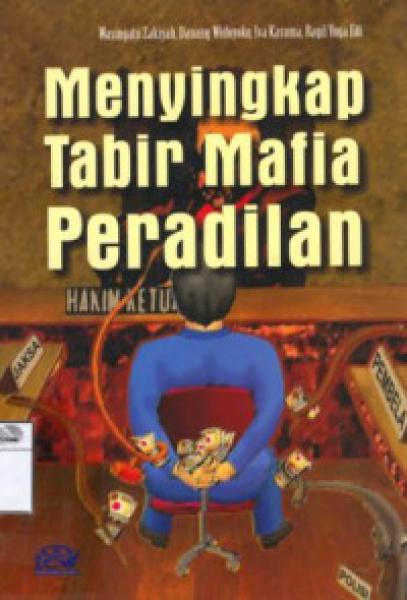
Aparat penegak hukum kembali berhasil membuka kotak pandora mafia peradilan di lembaga kekuasaan kehakiman. Kali ini, Kejaksaan Agung berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim itu ditangkap atas dasar tuduhan menerima suap dalam proses penanganan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur.
Tidak berhenti sampai di situ, penyidik berhasil mengembangkan informasi bahwa dalam perkara yang sama, terdapat upaya mempengaruhi proses hukum kasasi yang diajukan oleh Ronald Tanur. Benar saja, tidak lama berselang, pihak yang diduga sebagai makelar kasus akhirnya turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Zarof Ricar, mantan pejabat di Mahkamah Agung.
Penangkapan ini banyak menjadi perbincangan publik, sebab, dalam proses penggeledahan di rumah Zarof Ricar, penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk pecahan beberapa mata uang asing dengan total sekitar Rp920 miliar dan emas batangan seberat 51 kilogram. Belakangan diakui oleh Zarof bahwa uang tersebut berasal dari fee pengurusan sejumlah perkara yang dilakukannya dalam periode waktu tahun 2012 hingga tahun 2022.
Namun bagi pemerhati hukum, khususnya pemantau peradilan, penangkapan Zarof Ricar bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab modus yang dilakukan oleh Zarof serupa dengan yang dilakukan oleh jaringan mafia peradilan lainnya yang sebelumnya pernah diproses hukum oleh KPK, yakni Sekretaris MA, Nurhadi dan Hasbi Hasan. Sekalipun ketiganya bukan merupakan hakim atau pihak yang menangani perkara, namun dengan pengaruh besar yang dimiliki, mereka memperdagangkan pengaruh itu untuk menjadi perantara suap kepada hakim yang menangani perkara.
Modus ini juga setidaknya juga menjadi salah satu modus korupsi yang telah dipetakan oleh ICW sejak meluncurkan buku berjudul “Menyingkap Mafia Peradilan” pada tahun 2003 silam, mengartikan, bahwa modus korupsi di sektor peradilan tidak pernah berubah. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa, meski sudah pernah ada jaringan mafia peradilan yang diproses hukum, dan modus-modusnya sudah terpetakan, namun prakteknya masih ada hingga saat ini?
Menjawab pertanyaan tersebut, ada dua kemungkinan yang muncul. Pertama, proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK atau penegak hukum lainnya tidak pernah menyasar hingga aktor-aktor intelektualnya. Kedua, tidak ada upaya signifikan yang dilakukan oleh MA untuk melakukan upaya reformasi yang berdampak signifikan untuk menutup ruang gerak bagi hakim, panitera, atau pegawai pengadilan untuk melakukan praktik-praktik bertindak sebagai makelar kasus.
Kondisi ini tentu semakin menunjukkan bahwa moralitas para penegak hukum, khususnya hakim di lembaga peradilan, telah berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Maka tidak berlebihan rasanya jika publik, yang notabene merupakan para pencari keadilan, mengharapkan bahwa pengungkapan Zarof Ricar dijadikan sebagai momentum bagi penegak hukum untuk mengungkap jaringan mafia peradilan yang lebih luas di Mahkamah Agung.
Selain itu, penguatan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga otonom penjaga etika kehakiman juga perlu diperkuat. Sebab, prakteknya saat ini, Komisi Yudisial hanya dapat memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan aduan mengenai pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, dan kewenangan untuk memutusnya tetap di Mahkamah Agung. Sebagai langkah menghindari adanya potensi konflik kepentingan, maka Komisi Yudisial perlu diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada hakim.
Namun yang paling penting, agar simultan dengan strategi-strategi tersebut, perlu ada terobosan kebijakan dari Ketua Mahkamah Agung yang baru saja dilantik 22 Oktober 2024 lalu, Sunarto, untuk menjadi orkestrator dalam upaya mereformasi lembaganya guna mengembalikan kembali muruah lembaga peradilan.
Penulis: Diky Anandya
Editor: Agus Sunaryanto










