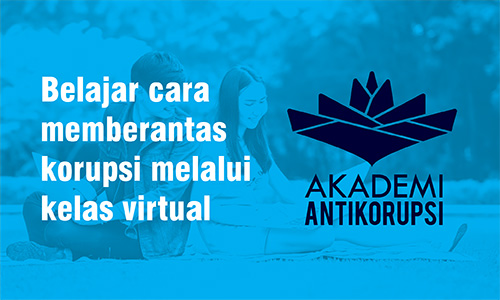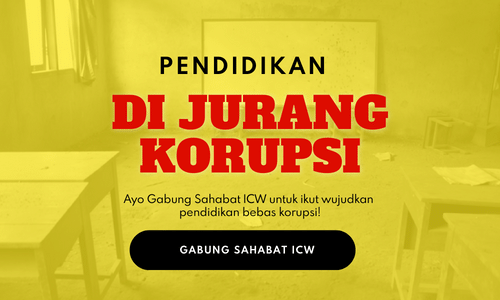Masyarakat Adat di Tengah Krisis Iklim: Korban atau Agen Perubahan

Krisis iklim merupakan ancaman paling mendesak bagi masa depan umat manusia sekaligus ancaman langsung terhadap hak asasi manusia (HAM). Dampak krisis iklim terus kita saksikan dan rasakan secara langsung seperti masalah kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola hujan, peningkatan intensitas bencana alam seperti badai tropis, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. Kondisi ini jelas mengancam sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati, yang merupakan dasar bagi kehidupan manusia, akhirnya masyarakat akan sangat dirugikan karena selain kehilangan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, masyarakat juga harus kehilangan mata pencaharian, produksi pangan, pemukiman, dan bidang lainnya yang vital bagi kesejahteraan manusia
Pada situasi seperti ini, masyarakat adat yang menopangkan hidup pada pada alam merupakan pihak yang paling dirugikan akibat krisis iklim, padahal mereka merupakan kelompok yang paling tidak bertanggung jawab menyebabkan krisis iklim (Doyle et al., 2022). Salah satu kerugian nyata akibat krisis iklim saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat adat di Kampung Adat Praijing, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dimana hasil panen masyarakat adat setempat merosot akibat musim kemarau Panjang yang menyebabkan lumbung pangan warga berkurang, bahkan tidak ada pasokan berlebih yang bisa dijual ke pasar sehingga daya beli masyarakat adat juga menurun (Kompas, 2024).
Berbagai upaya sedang dilakukan pemerintah untuk memerangi krisis iklim, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses transisi energi dengan mendorong pembangunan infrastruktur energi bersih dan energi terbarukan/EBET seperti pembangkit listrik tenaga (PLT) surya, PLT air, PLT panas bumi, dan PLT biomassa. Sayangnya, kebijakan yang berusaha ramah lingkungan ini nyatanya tidak ramah kepada masyarakat adat. Betapa tidak, pembangunan infrastruktur EBET membutuhkan lahan yang luas dimana sebagian besar lahan dan sumber daya alam yang dieksploitasi secara non-komersial, termasuk sumber utama energi terbarukan, ditemukan di dalam atau di sekitar wilayah masyarakat adat (Agrawal, et al., 2023), pada akhirnya masyarakat adat akan tergusur dari wilayahnya.
Salah satu contoh proyek energi terbarukan di Indonesia yang telah menggusur masyarakat adat dari tanah mereka, melanggar hak-hak masyarakat adat, mengakibatkan kerusakan lingkungan, budaya, spiritual, dan sosial yang sangat parah, serta konsekuensi kesehatan dapat ditemukan di Kepulauan Mentawai, dimana Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) bambu yang telah dibangun di Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 telah mengancam lingkungan hidup dan adat istiadat masyarakat Mentawai, eksploitasi hutan Mentawai menyebabkan beberapa daerah di Siberut dengan hulu lahan konsesi perhutanan saat ini menjadi zona langganan banjir (Trend Asia, 2023). Hal yang sama juga terjadi dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara, dimana proyek ini telah menenggelamkan dua desa, ribuan hektar lahan masyarakat adat, menerabas hutan, dan membendung air Sungai (The Conversation, 2023).
Krisis iklim dan kebijakan hukum yang tidak berpihak pada masyarakat adat selalu memposisikan masyarakat adat sebagai korban, padahal sejatinya masyarakat adat dapat menjadi agen perubahan berbekal pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat adat yang didukung dengan kebijakan hukum yang adil dan inklusif. Kebijakan hukum yang adil dan inklusif harus memastikan perlindungan HAM dan harus memastikan partisipasi yang setara bagi semua pihak, terutama masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait krisis iklim.
Keberhasilan masyarakat dayak di Desa Harowu Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam menerapkan energi bersih sebagai sumber elektrifikasi, merupakan buah dari kebijakan adil dan inklusif yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat sekaligus mempertimbangkan pengetahuan lokal masyarakat adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat dapat menjadi agen perubahan iklim yang membantu percepatan transisi energi dalam rangka memerangi krisis iklim, Bayangkan ada berapa banyak wilayah masyarakat adat yang memiliki potensi sumber energi terbarukan yang kemudian diberdayakan melalui kebijakan hukum yang adil dan inklusif dapat membantu percepatan transisi energi. Dengan kondisi demikian, bukan mustahil bagi Indonesia untuk mencapai target target bauran energi bersih 23 persen pada 2025 dan target nol emisi karbon pada 2060.
Membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam rencana transisi energi bermakna membuka kesempatan bagi pengakuan pengetahuan lokal masyarakat adat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menghormati kearifan lokal masyarakat adat, mewakili kebutuhan, aspirasi, dan pandangan masyarakat adat. Sayangnya, Indonesia belum sepenuhnya mendukung upaya ini. Hal ini terbukti dengan praktik konvensional dalam pembangunan proyek energi terbarukan, yang lebih didasarkan pada pendekatan top-down, dimana pemerintah pusat memimpin seluruh proses mulai dari proses penilaian rencana, pendanaan, pengadaan, dan pembangunan, dan menyerahkan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan yang telah selesai dibangun kepada pemerintah daerah sebagai langkah terakhir dalam pengembangan proyek sehingga menghambat partisipasi masyarakat adat di desa-desa terpencil (Ha & Kumar, 2021).
Pengabaian masyarakat adat dalam rencana transisi energi juga tampak dari tidak adanya regulasi di sektor energi yang secara khusus memasukkan persyaratan untuk mempertimbangkan pengetahuan lokal masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek energi terbarukan. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 56 Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT) yang mengatur mengenai partisipasi publik, yaitu hak masyarakat dalam kaitannya dengan pengusahaan energi terbarukan, dimana tidak satu kata pun dari bunyi pasal tersebut yang menyebutkan secara khusus mengenai masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat juga tidak diatur pada tingkat peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) maupun pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022).
Berkaca pada negara lain, Kanada memiliki perangkat hukum yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, yaitu The Canadian Pact for A Green New Deal yang menghubungkan transisi energi dengan tujuan mencapai rekonsiliasi dengan masyarakat adat (O'Neill et al., 2021). Melalui kebijakan tersebut, hasil penelitian mencatat perkiraan keuntungan sebesar $2,5 miliar bagi komunitas masyarakat adat selama 15 tahun, dan keuntungan bersih tahunan sebesar $167 juta dari proyek energi terbarukan, laporan ini juga mencatat 299 orang masyarakat adat bekerja di bidang energi terbarukan, dan perkiraan pendapatan pekerjaan masyarakat adat sebesar $842 juta. (Thorburn et al., 2017).
Indonesia hendaknya belajar dari kesuksesan Kanada dalam membentuk kebijakan transisi energi yang adil dan inklusif yang pada praktiknya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Untuk itu, pemerintah perlu memposisikan masyarakat adat sebagai agen perubahan dengan membuat suatu regulasi yang secara komprehensif mengatur partisipasi berarti dan bermakna dari masyarakat adat dalam rencana transisi energi sebagai salah satu upaya memerangi krisis iklim.
Penulis,
Dea Tri Afrida
Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum / Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas
*Artikel Sayembara Opini Antikorupsi 2024