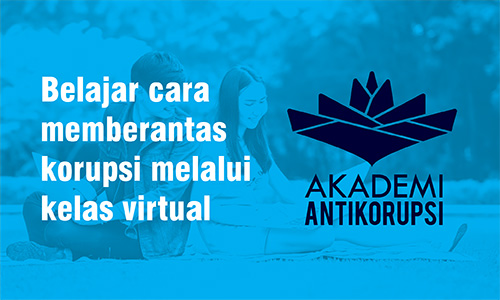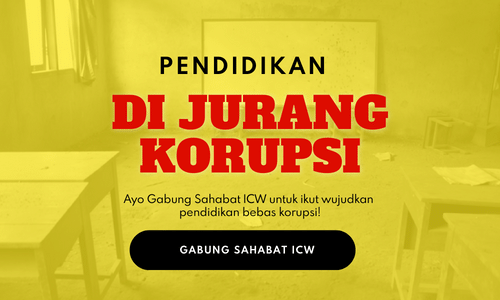“Hak atas Pangan Bukan Sumber Cuan”
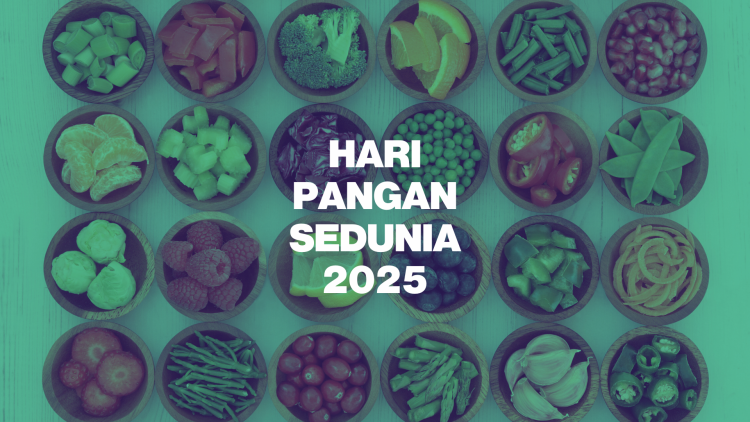
Jakarta, 15 Oktober 2025 — Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober seharusnya menjadi momentum refleksi atas mandat konstitusional untuk menjamin hak rakyat atas pangan yang cukup, sehat dan bergizi. Namun dalam praktiknya, kebijakan pangan nasional berupa “Swasembada Pangan” justru memperlihatkan kecenderungan komodifikasi, komersialisasi dan militerisasi pangan, yang justru semakin menjauhkan rakyat dari kedaulatan atas pangan dan sumber-sumber kehidupan mereka.
Rezim Pangan Korporat sebagai Problem Utama
Sejak Hari Pangan Dunia ditetapkan oleh FAO pada tahun 1979, narasi global yang dibangun, lebih menekankan pada ketahanan pangan bukan kedaulatan pangan. Konsep ketahanan pangan yang digaungkan tidak menempatkan produsen pangan seperti petani kecil, nelayan tradisional dan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam sistem pangan. Sebaliknya justru mendorong pemenuhan pangan yang bergantung pada pasar bebas dan fluktuasi harga. Aspek keberlanjutan dan kedaulatan hak atas pangan pun tidak menjadi prioritas dalam konsep ketahanan pangan. Secara global Laporan FAO 2025 menyatakan masih terdapat 673 juta jiwa manusia yang berada dalam kondisi kelaparan dan 2,6 miliar manusia tidak mampu membeli pangan yang sehat dan bergizi. Situasi ini terjadi karena multi krisis yang disebabkan ketidakadilan struktural dalam sistem pangan dimana korporasi mendapatkan keuntungan namun sebaliknya bagi produsen pangan skala kecil.
Pasca-reformasi, Indonesia mulai mengimajinasikan ‘kondisi terpenuhinya pangan’ dalam definisi ketahanan pangan dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan. Kata kunci ‘terpenuhinya’ menautkan ketersediaan pangan dengan mengandalkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar menjadi alat efisiensi ekonomi pangan baik akses, ketersediaan maupun harga. Karena itu, impor pangan sebagai bagian dalam efisiensi ekonomi pangan seakan ‘masuk akal’. Konsep ketahanan pangan memberikan ruang terbuka terhadap impor dalam menekan harga pangan dalam negeri sekaligus menggerogoti kedaulatan pangan. Sementara kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Produsen Pangan dalam UU No. 19/2013 dan UU No. 7/2016 tidak dijalankan bahkan cenderung diabaikan seperti mandat reforma agraria dalam UU Pokok Agraria.
Rezim pangan korporat berjalan dalam kebijakan pangan Indonesia seiring masuknya konsep ketahanan pangan. Dalam rezim ini, korporasi besar menjadi aktor utama ketahanan pangan. Melalui pola pertanian pangan industrial, korporasi berperan utama dalam penyediaan pangan berskala besar, efisien, dan murah (McMichaels 2011, 2021). Dalam pola produksi tersebut, korporasi mengandalkan produksi berbasis padat modal, lahan berskala luas, monokultur, dan padat kimia. Melalui Paradigma ini, sembari memanfaatkan sisa-sisa warisan Revolusi Hijau, FAO dan lembaga-lembaga lainnya mendorong peningkatan produksi pangan dengan teknologi modern dan integrasi ke dalam mekanisme pasar bebas.
Di Indonesia, proyek tersebut gagal mensejahterakan petani kecil, karena memperdalam ketimpangan penguasaan lahan dan memperkuat posisi korporasi pangan besar. Pemerintah Indonesia memanfaatkan kegagalan Revolusi Hijau sebagai alasan untuk memperluas konsesi lahan perkebunan sawit dan karet skala besar, terutama bagi korporasi transnasional. Sejak saat itu, kebijakan pangan nasional berpihak pada bisnis dan modal, bukan pada rakyat. Kedaulatan pangan diberangus, yang tersisa adalah sistem pangan yang dikendalikan oleh pasar dan kekuasaan. Rakyat pun kembali menjadi penonton atas hilangnya hak mereka atas tanah, benih, dan masa depan yang layak.
Ekspansi Sawit, Krisis Ekologi, dan Hilangnya Akses terhadap Pangan
Ekspansi perkebunan sawit skala luas telah menjadi salah satu faktor utama yang memperdalam krisis pangan dan ekologi di Indonesia. Proyek-proyek perkebunan yang digadang-gadang sebagai sumber devisa dan pembangunan daerah, pada kenyataannya menimbulkan perampasan lahan (land grabbing), penggusuran paksa, serta ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap satu komoditas ekspor yang tidak menjamin kedaulatan pangan.
Di banyak wilayah, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, masyarakat kehilangan kebun pangan dan hutan adat mereka yang selama ini menjadi sumber pangan, obat, dan air bersih. Sungai-sungai tercemar limbah pabrik sawit, menyebabkan ikan menghilang dan air tidak lagi layak konsumsi. Paparan bahan agrokimia berbahaya dari aktivitas perkebunan berdampak pada kesehatan masyarakat. Kekeringan dan banjir menjadi siklus tahunan akibat deforestasi dan rusaknya ekosistem penyangga.
Krisis pangan hari ini bukan disebabkan oleh kurangnya produksi, melainkan oleh ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dan korupsi dalam tata kelola sumber daya alam. Lahan-lahan subur dikuasai oleh korporasi besar melalui konsesi jangka panjang, sementara petani kecil kehilangan tanah dan buruh perkebunan hidup tanpa jaminan. Termasuk nelayan tradisional skala kecil yang kehilangan hak-hak akses dan kontrol terhadap perairan untuk perikanan dengan sistem penangkapan ikan terukur dan perampasan laut.
Dari Hak Dasar ke Komoditas Politik
Sampai hari ini, pangan sebagai hak dasar belum menjadi arus utama dalam paradigma Negara cq. pemerintah Indonesia. Persoalan pangan lebih sering ditempatkan dalam bingkai politik dan ekonomi yang menempatkan pangan semata sebagai komoditas pasar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dua proyek besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Food Estate, menjadi potret paling terang dari bagaimana negara menjauh dari prinsip hak atas pangan dan gizi serta kedaulatan rakyat atas sumber kehidupannya.
Melalui proyek MBG, pemerintah tampak memposisikan pangan sebagai komoditas populis dan kendaraan politik. Program yang seharusnya menjamin gizi rakyat justru dikelola secara sentralistik tanpa partisipasi publik yang bermakna, ditujukan kepada kelompok yang paling marjinal dan tanpa keberpihakan pada produsen pangan lokal. Koalisi Tolak MBG, menyebutkan Proyek MBG ini tidak memenuhi aspek hak atas pangan, mulai dari transparansi, pelaksanaan secara progresif, ketersediaan pangan bermutu, kelayakan gizi, keamanan pangan, aksesibilitas ekonomi, hingga keberlanjutan hukum dan keadilan atas anggaran yang tidak akuntabel dan transparan.
Bahkan proyek Food Estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah hingga Merauke-Papua Selatan memperparah situasi. Dengan dalih menjawab krisis pangan dengan efisiensi dan produktivitas, negara justru menciptakan krisis dengan melanggengkan perampasan tanah, pemusnahan benih lokal, dan penyingkiran masyarakat adat dan petani dari ruang hidupnya. Pemantauan FIAN Indonesia di Kalimantan Tengah menunjukkan tiga bentuk pengingkaran negara terhadap hak atas pangan dan gizi, negara gagal menghormati, gagal melindungi, dan gagal memenuhi hak atas pangan bagi rakyat. Temuan yang sama yang dilakukan oleh Pantau Gambut mengungkap penelantaran area gambut yang telah dibuka dengan luasan yang masif. Di tengah krisis iklim yang semakin parah, keberlanjutan program Food Estate menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, karhutla masih terus terjadi sejak tahun 1997 dan melepaskan ratusan ribu ton karbon dioksida ke udara di kawasan eks-PLG ini. Kegagalan yang nampak terang benderang dan ancaman ledakan ‘bom karbon‘, seharusnya bisa menyadarkan pemerintah akan rapuhnya ekosistem ini. Sayangnya, fakta ini tetap tak menghentikan pemerintah Indonesia untuk melakukan perluasan (ekstensifikasi) area Food Estate hingga saat ini.
Militerisasi Pangan dan Konflik Kepentingan di Balik Program Pemerintah
Di tengah krisis pangan dan lingkungan, pemerintah Indonesia justru memperluas peran aparat keamanan dan militer dalam pengelolaan sektor pangan. Sejumlah lembaga dan program strategis seperti PT Agrinas Palma Nusantara, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dan Proyek MBG, dijalankan dengan kontrol tinggi dari unsur militer tanpa mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik yang jelas. Anggapan bahwa pangan sebagai bagian ketahanan nasional yang bisa diintervensi aparat keamanan dan militer adalah kesesatan dan kesalahan berpikir yang nyata.
Kasus PT Agrinas Palma Nusantara menunjukkan bagaimana militerisasi ekonomi pangan gagal melindungi rakyat. Setelah mengambil alih kebun eks-PT Duta Palma, perusahaan ini gagal memenuhi hak-hak buruh dan gagal memulihkan hak atas pangan. Satgas PKH, yang seharusnya menertibkan kawasan hutan, justru memperburuk konflik agraria di berbagai wilayah karena pengambilalihan lahan dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan disertai intimidasi aparat.
Kecenderungan serupa tampak dalam proyek MBG. Meski belum ditemukan kasus korupsi, potensi konflik kepentingan dan rente politik sangat kuat, karena proyek ini dikelola secara sentralistik tanpa memperkuat produsen pangan lokal. Mekanisme distribusi yang tertutup membuka ruang bagi jaringan bisnis dan elite politik untuk mengambil keuntungan dari proyek populis tersebut.
Kondisi ini menegaskan pola lama dalam tata kelola pangan Indonesia. Sektor pangan kerap menjadi lahan basah konflik kepentingan dan korupsi politik, seperti terlihat dari kasus korupsi impor sapi (2013), korupsi beras bansos (2020), dan impor pangan “bal-balan”. Pola ini menunjukkan bagaimana pangan dijadikan alat transaksi kekuasaan, bukan pemenuhan hak rakyat.
Pangan, Perempuan, dan Ketimpangan Struktural
Hilangnya lahan, kenaikan harga pangan, dan proyek-proyek korporasi yang maskulin dan militeristik membuat peran perempuan dalam produksi pangan domestik terpinggirkan. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka lebar peluang impor pangan tanpa mempertimbangkan kedaulatan dan ketersediaan pangan nasional juga memperparah posisi perempuan yang selama ini menjadi subjek utama dalam pengelolaan pengetahuan pangan lokal dan keberlanjutan sumber pangan di komunitas.
Perempuan sudah banyak melakukan inisiatif untuk keberlanjutan pangan di komunitas, misal dalam merespon krisis iklim, Perempuan di Sumba, Nusa Tenggara Timur melakukan inisiatif menggunakan ubi beracun (uwi/iwi) sebagai pengganti beras saat terjadi kemarau berkepanjangan dan gagal panen untuk dapat bertahan hidup. Hal ini juga dilakukan oleh perempuan kulon progo yang menggunakan praktik pertanian lestari dengan penggunaan bibit lokal, pupuk organik dan sistem kalender tanam tradisional sebagai kritik terhadap sistem pertanian konvensional yang kerap menggunakan teknologi bias gender dan abai terhadap lingkungan.
Selama sistem pangan masih berorientasi pada industri pangan skala besar, menggunakan pembangunan pangan yang patriarkal dan hanya berbasis proyek, maka perempuan hanya akan tersingkirkan dari ruang pengambilan keputusan, memperkuat ketimpangan gender, dan diabaikan hak-hak ekonominya. Setidaknya sebanyak 3.624 perempuan dari 57 desa di Indonesia mengalami penindasan dan pemiskinan akibat dari situasi ini yang kemudian berdampak pada krisis pangan, rusaknya lingkungan dan hilangnya keragaman pangan lokal (Catahu Solidaritas Perempuan, 2025).
Alih-alih meningkatkan produktivitas sistem pangan yang dikelola oleh perempuan, negara justru semakin menjauhi semangat dan prinsip keadilan. Situasi ini tentu menunjukkan bahwa krisis pangan juga merupakan krisis gender, di mana struktur patriarki dalam kebijakan dan praktik pembangunan pangan menyingkirkan peran, suara, dan kepemilikan perempuan atas sumber-sumber kehidupan. Terlebih, hingga hari ini Negara tidak mengakui perempuan sebagai pemangku hak atas pangan selayaknya produsen pangan dalam berbagai kebijakan pertanian maupun perikanan.
Benih, Liberalisasi Pasar, dan Ancaman atas Kedaulatan Pangan
Krisis pangan global hari ini bukan semata soal kurangnya produksi, tetapi tentang siapa yang menguasai sumber daya pangan dan siapa yang diuntungkan dari sistem pangan dunia. Sayangnya, kebijakan pangan Indonesia kini justru bergerak dalam arus yang sama—terperangkap dalam logika pasar global melalui skema seperti Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I–EU CEPA). Salah satu ancaman paling nyata dari perjanjian semacam itu adalah tekanan agar Indonesia bergabung dengan Konvensi UPOV 1991 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), yang memberi hak monopoli atas benih kepada korporasi dan melarang petani untuk menyimpan atau menukar benih mereka sendiri. Terlebih Mahkamah Konstitusi telah menegaskan hak-hak petani kecil sebagai pemulia benih.
Ditambah lagi ancaman melonjaknya komoditas pertanian yang akan masuk dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah Indonesia menyetujui kesepakatan dagang dengan AS di mana komoditas pangan dan pertanian AS akan dibebaskan dari bea masuk (tarif). Selain hal ini tidak dikonsultasikan secara bermakna dengan rakyat khususnya produsen pangan seperti petani dan nelayan, kesepakatan ini hanya akan menambah lapisan kompetisi produk lokal dengan komoditas pangan impor. Dengan ini Indonesia terancam dilemahkan kapasitasnya untuk meregulasi komoditas impor demi melindungi petani skala kecil. Kewajiban untuk memenuhi standarisasi yang tertuang di berbagai perjanjian perdagangan juga mempersulit petani kecil untuk memenuhinya, sehingga Indonesia akan terjebak pada korporatisasi pangan dan kehilangan kedaulatan untuk mengatur standar keamanan dan kualitas pangan domestik. Situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam Swasembada pangan yang diinginkan dengan tindakan Presiden Prabowo.
Padahal sejatinya, pangan berkelanjutan hanya mungkin terwujud jika negara melindungi sistem pangan rakyat, memperkuat pengetahuan lokal, dan menolak komersialisasi benih serta liberalisasi pasar yang menyingkirkan petani kecil, nelayan, dan perempuan produsen pangan dari rantai nilai. Kedaulatan pangan bukan cita-cita utopis, tapi syarat mutlak bagi kemerdekaan bangsa atas sumber pangannya sendiri.
Dari uraian di atas, Koalisi PACUAN menuntut untuk:
- Menegakkan kedaulatan pangan ke tangan rakyat dengan memastikan hak atas pangan dan gizi dijalankan melalui reforma agraria, perlindungan lingkungan, dan dukungan bagi sistem pangan lokal yang berkeadilan;
- Menghentikan militerisasi sektor pangan, termasuk penguasaan lembaga dan BUMN pangan oleh aparat militer;
- Menghentikan dan mengevaluasi Proyek MBG dan Food Estate;
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas program pangan nasional;
- Menegakkan hak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat baik perempuan dan laki-laki terhadap tanah serta sumber-sumber agraria yang terkait dengan pangan;
- Memastikan keterlibatan bermakna komunitas produsen pangan skala kecil yaitu petani kecil, nelayan tradisional dan masyarakat adat dalam setiap perumusan kebijakan pangan;
- Menindak tegas praktik konflik kepentingan dan korupsi dalam tata kelola pangan nasional;
- Menghentikan eksploitasi gambut dan rehabilitasi ekosistem gambut yang terdegradasi;
- Menghentikan liberalisasi pertanian yang mengebiri hak petani dan memperlemah kedaulatan pangan lokal.
Krisis pangan yang kita hadapi bukan sekadar soal kekurangan makanan, melainkan soal siapa yang menguasai tanah, benih, dan kebijakan pangan itu sendiri. Selama pangan diperlakukan sebagai komoditas politik dan alat kontrol kekuasaan, rakyat akan terus lapar, bukan karena gagal menanam, tetapi karena haknya dirampas.
Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 menjadi seruan bagi kita semua untuk mendobrak struktur korup, patriarkal, dan militeristik yang membelenggu sistem pangan nasional, serta mengingkari perwujudan hak atas pangan dan gizi.
Narahubung:
Mufida (+6281287717826)
Putra (+6285372626017)
Koalisi Pangan Anti Cuan
FIAN Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Sajogyo Institute, Transparency International Indonesia (TII), Solidaritas Perempuan, Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Indonesia for Global Justice (IGJ), Pantau Gambut, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi.