Pendidikan Tinggi Melawan Korupsi
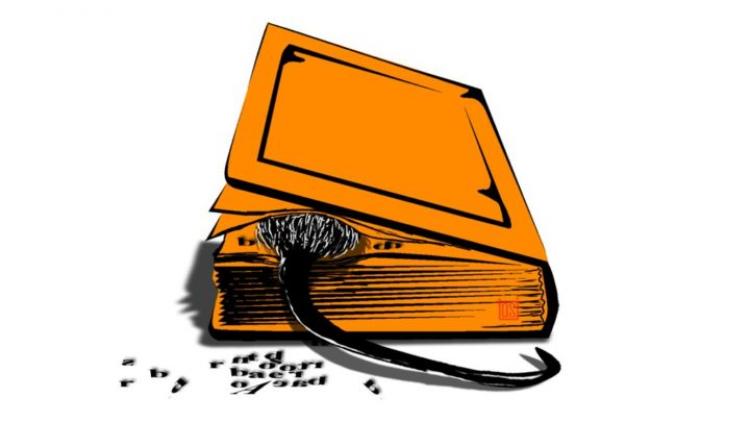
Tahun 2017 dilalui dengan kehebohan penanganan beberapa kasus korupsi. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah ditutup dengan ditangkapnya ketua lembaga legislatif pada November lalu. Kehebohan semacam itu diprediksi akan terus berlanjut karena korupsi masih menjadi penyakit sosial yang belum tersembuhkan.
Situasi itu harus dipandang sebagai persoalan kebangsaan secara luas, bukan persoalan hukum semata. Oleh karena itu, tiap elemen masyarakat wajib merefleksikan diri agar ke depan dapat memberi kontribusi yang lebih berarti, termasuk masyarakat pendidikan tinggi.
Bagi masyarakat pendidikan tinggi, korupsi dapat disikapi dari dua perspektif. Pertama, korupsi dipandang sebagai realitas sosial yang dibaca sebagai sumber pengetahuan. Pola, perubahan, dan anatomi korupsi ditempatkan sebagai gejala yang netral sebagaimana realitas sosial lain. Membaca korupsi adalah bagian dari usaha memahami realitas dunia yang kompleks dan terus berubah.
Kedua, korupsi dipandang sebagai realitas yang harus diintervensi karena bertentangan dengan nilai dasar pendidikan. Masyarakat pendidikan meyakini bahwa kejujuran adalah nilai universal yang sangat mendasar. Korupsi adalah praktik culas yang bukan saja bertentangan dengan nilai itu, melainkan juga merupakan ancaman terhadap terwujudnya masyarakat ideal.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, kerugian negara akibat korupsi selama semester I-2017 mencapai Rp 1,83 triliun. Kerugian sebesar itu merupakan kendala nyata yang menyebabkan masalah pembangunan terhambat dan cita-cita keadilan semakin jauh dari jangkauan. Padahal, masyarakat pendidikan mendambakan terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera.
Lebih dari itu, Chapman (2002) menunjukkan bahwa korupsi juga menyebabkan kebangkrutan moral yang parah. Anak muda yang melihat korupsi dalam kesehariannya akan terdistorsi persepsi ideologisnya, mengira bahwa kesuksesan tidak diraih dengan kerja keras, tetapi dengan penyuapan dan kecurangan. Kondisi itu akan melemahkan basis nilai masyarakat, sendi kehidupan masyarakat sipil, baik sekarang maupun masa depan.
Di luar dua perspektif itu, pendidikan tinggi adalah lembaga publik yang tata kelolanya di bawah birokrasi pemerintahan. Pendidikan tinggi, sebagaimana lembaga publik lain, adalah institusi yang rentan menjadi korban sekaligus pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sangat penting perguruan tinggi untuk mengembangkan gagasan hukum agar korupsi bisa dihapus dari bumi Pertiwi.
Tiga perspektif di atas menempatkan perguruan tinggi pada dua posisi sekaligus: subyek dan obyek. Sebagai subyek, perguruan tinggi merupakan entitas sosial yang memiliki kehendak dan memiliki daya untuk mewujudkan kehendaknya. Adapun sebagai obyek, perguruan tinggi berposisi sebagai bagian kecil dari sistem besar birokrasi yang kompleks. Dalam posisi kedua ini, kehendak perguruan sangat dibatasi sistem yang membawahinya.
Kekuatan moral
Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi mendapatkan tugas yang sangat spesifik untuk melaksanakan tri darma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, secara historis, perguruan tinggi memiliki peran yang lebih mendasar, yaitu peletak nilai dalam kehidupan berbangsa.
Tugas besar ini tampaknya diwarisi sejak lembaga berbentuk perguruan tinggi mulai dikenal. Academy-nya Plato yang didirikan 387 SM di Athena melahirkan pemikir yang gagasannya berkembang menjadi nilai bersama. Alumninya mendedikasikan pengetahuan bagi terciptanya komunitas yang lebih baik. Karena itulah, Academy diapresiasi luas oleh masyarakat sebagai penjaga moral masyarakat bersama kaum rohaniwan.
Pada era seperti saat ini, perguruan tinggi berkembang dengan variasi yang luar biasa banyaknya. Dalam masyarakat yang kian kompleks, tentu saja perguruan tinggi juga mengalami perkembangan dan perubahan. Akan tetapi, ekspektasi publik agar perguruan tinggi menjadi penjaga moral masyarakat dan bangsa tidak pernah berubah.
Dalam kaitannya dengan korupsi, lembaga pendidikan sering kali disebut sebagai harapan terakhir bersama KPK. Pendapat ini berpangkal pada asumsi bahwa penindakan secara hukum tak akan bisa mengatasi korupsi hingga akar persoalannya. Karena lebih banyak korupsi adalah perkara integritas, pembentukan budi pekerti luhur adalah solusinya.
Selama ini perguruan tinggi telah banyak melahirkan pendekar antikorupsi, cendekia yang dengan kesungguhan mendermakan energi dan pemikirannya untuk melawan korupsi. Ada tokoh besar, seperti (untuk sekadar menyebut beberapa nama) Mahfud MD dan Artidjo Alkostar (UII), Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar (UGM), serta Saldi Isra (Unand).
Akan tetapi, kiprah mereka secara individual tidak cukup strategis untuk melawan korupsi yang telanjur masif. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi harus terlembaga, terencana, dan berkelanjutan.
Catatan menunjukkan sekitar 80 persen pelaku tindak pidana korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Meskipun ini aib yang memalukan, perguruan tinggi tidak perlu membantah. Sebaliknya, catatan itu patut dijadikan sarana merefleksikan diri agar ke depan dapat mengembangkan pendidikan yang baik agar setiap alumnus yang diluluskannya adalah pendekar antikorupsi.
Aturan dan budaya
Untuk memastikan lahirnya alumni antikorupsi, tentu saja perguruan tinggi harus memastikan bahwa dirinya sendiri antikorupsi. Ikhtiar ini telah dan terus dilakukan dengan dua cara, yaitu menyiapkan aturan yang ketat dan membangun budaya akademik yang berintegritas. Dua pendekatan ini tidak bisa saling dipisahkan karena bersifat resiprokal, saling menguatkan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemeristek dan Dikti) telah menerbitkan aturan untuk memastikan perguruan tinggi mewujudkan tata kelola yang baik (good governance university). Aturan itu disambut oleh masing-masing perguruan tinggi dengan aturan pelaksanaan sesuai karakter dan kebutuhan spesifiknya. Aturan itu membentang mulai dari pengelolaan keuangan hingga penulisan karya ilmiah.
Berbagai aturan itu, baik langsung maupun tidak langsung, berdampak pada terciptanya kultur akademik yang lebih berintegritas. Dalam tata kelola kelembagaan, misalnya, universitas telah bersikap transparan sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemanfaatan teknologi informasi juga membuat pengelolaan semakin efisien.
Dua hal itu idealnya saling melengkapi sehingga berdampak nyata terhadap terciptanya lulusan perguruan tinggi antikorupsi. Meski arah menuju itu tampak akan berat dan berliku, ikhtiar menuju titik itu harus terus dijaga. Betapa pun kecilnya, usaha untuk mewujudkan kondisi itu harus diapresiasi.
Fathur Rokhman Rektor Universitas Negeri Semarang
Tulisan ini disalin dari Kompas, 12 Januari 2018










