ICW Luncurkan Buku Simalakama Kawasan Hutan
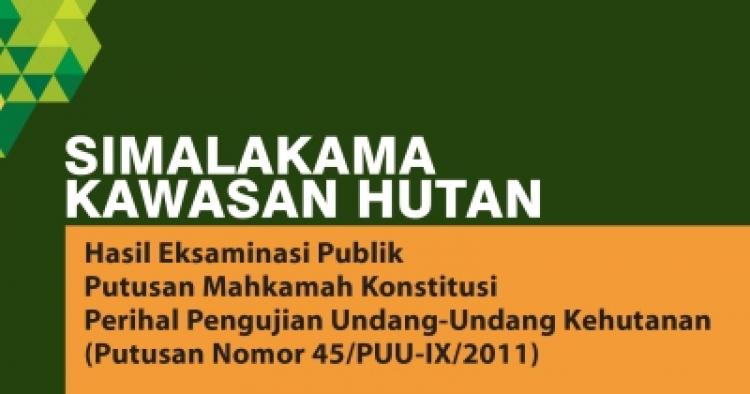
Status kawasan hutan selalu menjadi perdebatan tanpa ujung, terutama soal penegakan hukum dan kelestarian lingkungan, karena definisi kawasan hutan adalah landasan bagi penatagunaan dan pengelolaan kawasan hutan.
Pada Bulan Februari tahun 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian tentang definisi kawasan hutan dalam UU Kehutanan, yang dimohon oleh lima Bupati Kalimantan Tengah dan satu warga Palangkaraya.
Menurut para pemohon, dalam negara hukum, pejabat tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, tapi harus sesuai hukum. Pemohon juga menyatakan bahwa tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap dan menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan.
Pasal yang diuji adalah pasal 1 angka 3 UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Menurut para pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945.
Akhirnya, MK mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya, sehingga frasa “ditunjuk dan atau” dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan MK mengubah definisi kawasan hutan yang awalnya berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” menjadi: “Kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
Pengujian konstitusionalitas kawasan hutan sebenarnya adalah peluang emas untuk mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan hutan. Namun, kesempatan ini tidak dimanfaatkan MK secara maksimal.
Masyarakat adat pun tidak dijadikan pertimbangan dalam hampir setiap kasus kriminalisasi akibat ketidakpastian hukum. Meskipun sudah ada usaha peningkatan penetapan kawasan hutan, tapi koalisi menilai bahwa masyarakat adat belum menjadi prioritas negara, padahal penerapan kawasan hutan ini adalah pangkal masalah kriminalisasi masyarakat adat.
Setelah melakukan eksaminasi terhadap putusan ini sepanjang 2012, pada 14 Februari lalu di Jakarta, ICW yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan menyelenggarakan diskusi yang membahas hasil eksaminasi serta meluncurkan buku “Simalakama Kawasan Hutan” yang berisi hasil eksaminasi lengkap.
Narasumber diskusi adalah Yance Arizona akademisi dari Epistema Institute yang tergabung dalam Majelis Eksaminasi, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang turut bergabung memberikan catatan terhadap hasil eksaminasi, dan Tri Joko dari Kementerian Kehutanan yang membahas dampak putusan MK ini terhadap isu kawasan hutan di Indonesia.
Hasil eksaminasi mengungkap banyak temuan menarik. Pertama, koalisi menilai bahwa putusan MK tergolong putusan yang cepat diputus dan cukup tergesa-gesa
Kedua, putusan MK punya implikasi bahwa kawasan hutan sama dengan hutan negara. Padahal, dalam UU Kehutanan, kawasan hutan tidak diidentikkan dengan hutan negara. UU Kehutanan membagi status hutan menjadi hutan negara dan hutan hak, termasuk hutan adat.
Konsekuensi hukum putusan MK menyebabkan ketentuan tentang hutan hak menjadi tidak relevan lagi, termasuk hak bagi pemegang hak atas tanah untuk mengelola hutan, dan hak bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya. Di sisi lain, hak untuk mengakses hutan pun seolah-olah dinegasikan dengan putusan ini, di mana kawasan hutan digambarkan sebagai tanah tak bertuan yang harus bebas dari manusia (terra nullius).
Ketiga, hakim konstitusi menerapkan penafsiran sistematis dan restriktif, untuk membatasi diri pada soal pendefinisian kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Hakim konstitusi tidak meletakkan perihal pendefinisian kawasan hutan sebagai salah satu inti sengkarut tata kelola kehutanan.
Keempat, MK tidak mendalami peristiwa konkret yang mendasari pemohon mengajukan pengujian. Memang, desain kewenangan MK bukanlah mengadili peristiwa konkret, melaiunkan norma hukum dalam undang-undang. Tetapi, putusan ini harusnya bisa memberikan efek perbaikan.
Berdasarkan hasil eksaminasi, koalisi memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.
Pertama, MK seharusnya berusaha lebih jauh ketimbang melakukan interpretasi gramatikal restriktif terhadap frasa “dan atau ditunjuk”. Proses interpretasi norma harus digali dengan cakrawala yang lebih luas.
Kedua, MK perlu mendalami peristiwa konkret yang mendasari permohonan pengujian. Pendalaman ini dapat memberi arahan penyelesaian peristiwa konkret tersebut dan dapat menuntun penyelesaian peristiwa serupa di kemudian hari.
Ketiga, dengan dihapusnya frasa “ditunjuk dan atau” yang menyebabkan berubahnya definisi kawasan hutan, maka ada dua poin yang koalisi cermati, yaitu: Kementerian Kehutanan harus segera mempercepat pengukuhan kawasan hutan, dan dalam prosesnya, pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara otoriter, represif, dan non partisipatif.
Keempat, pemerintah harus tetap melanjutkan proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan. Penegak hukum harus memahami bahwa MK tidak membatalkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan.
Kelima, MK perlu memperlakukan sama para pihak dalam proses persidangan, baik pihak terkait maupun pemohon, karena para pihak memiliki alasan-alasan konstitusional untuk mengajukan permohonan.
Eksaminasi publik dilakukan ICW yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, pada bulan Juli sampai Oktober 2012 lalu. Eksaminasi dilakukan para ahli yang terdiri dari Yance Arizona (Epistema), Grahat Nagara (Silvagama), Hermsansyah (Universitas Tanjung Pura Pontianak), Hariyadi (Dewan Kehutanan Nasional/ DKN), Nordin (Save Our Borneo), Trihayati (Universitas Indonesia), Rhino Subagyo (Peneliti), Shinta Agustina (Universitas Andalas), Adriani Zakaria (Peneliti isu Perkebunan).










